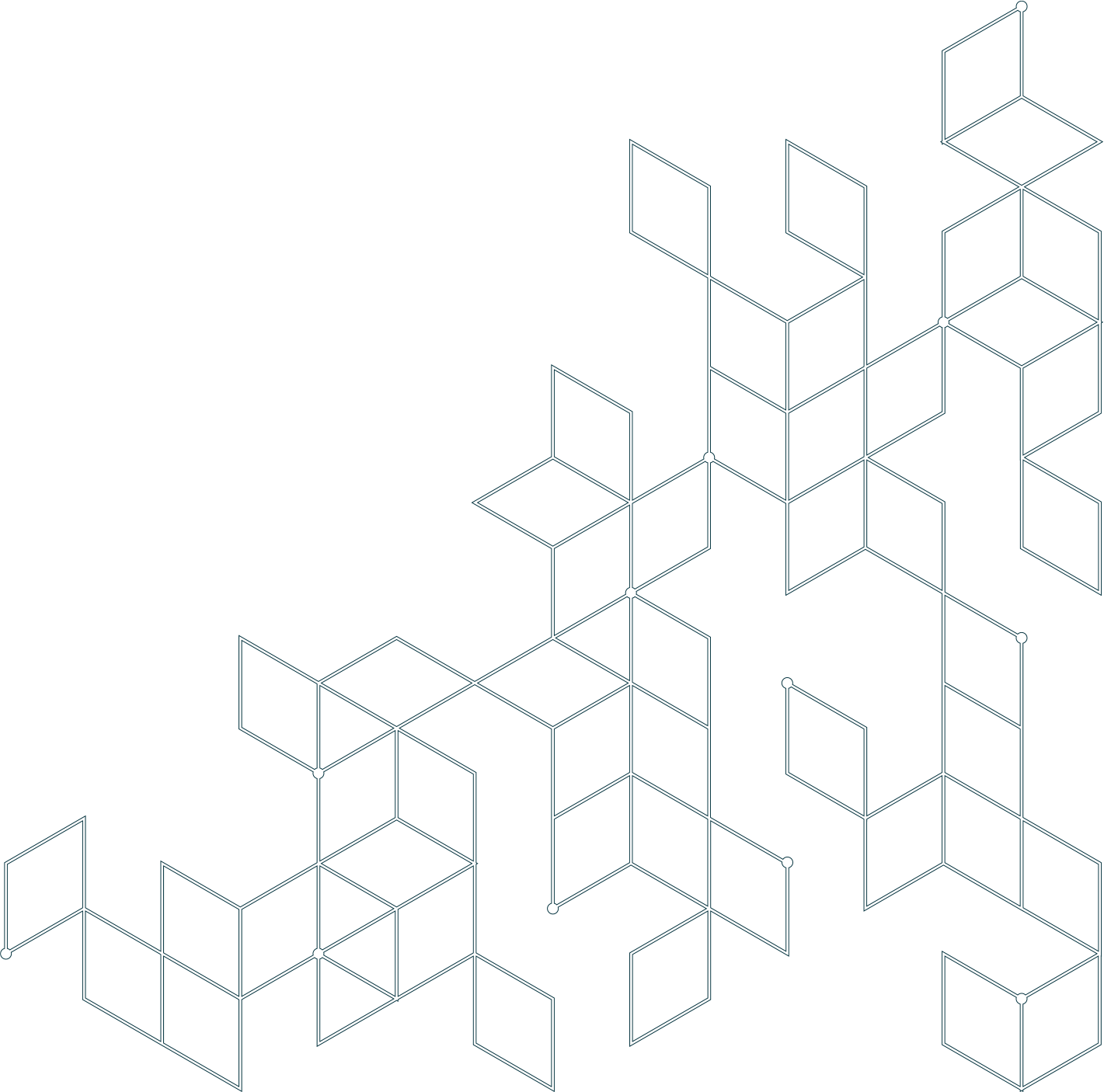
Deadline for submission: 1 Aug 2025

Sejak 2014, industri pertambangan nikel di Indonesia berkembang pesat, seiring kebijakan hilirisasi mineral dan pembangunan smelter di berbagai wilayah, terutama Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Saat ini terdapat 345 izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang mencakup hampir 1 juta hektare, dengan lebih dari 478 ribu hektare masih berupa hutan. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan deforestasi besar-besaran, tetapi juga mengancam 26 unit konservasi seluas 452 ribu hektare yang terletak di dalam wilayah deposit nikel. Di tengah transisi hijau global, Indonesia menghadapi sebuah paradoks: meningkatnya tekanan terhadap hutan, wilayah pesisir, dan masyarakat lokal akibat ekspansi industri pertambangan nikel yang masif dan tidak terkendali.
Pertambangan, khususnya nikel, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekspor nasional dan produk domestik bruto (PDB), khususnya dari sektor industri hilir seperti smelter. Namun, kontribusi fiskal ini sering tidak diimbangi dengan regulasi lingkungan dan sosial yang memadai. Banyak wilayah pertambangan justru mengalami kerusakan ekosistem, konflik sosial, dan hilangnya fungsi ekologis yang lebih bernilai dalam jangka panjang. Argumen bahwa tambang menyerap banyak tenaga kerja perlu dilihat secara kritis. Di banyak kasus, tenaga kerja lokal hanya terserap di level pekerjaan kasar, sementara posisi teknis dan manajerial diisi oleh tenaga dari luar daerah. Selain itu, pekerjaan di sektor tambang bersifat tidak berkelanjutan, bergantung pada umur tambang dan sering berakhir dengan pemutusan hubungan kerja tanpa pemulihan ekonomi lokal yang jelas.
Pertambangan nikel menyebabkan perubahan bentang alam secara drastis, mulai dari pembukaan hutan, pengerukan tanah, pembangunan jalan tambang, hingga pembuatan kolam limbah. Di Sulawesi Tengah dan Tenggara, penebangan hutan untuk tambang dan smelter berdampak langsung terhadap banjir bandang, tanah longsor, dan sedimentasi sungai. Foto-foto satelit dan lapangan menunjukkan bagaimana kawasan yang dulunya hijau kini berubah menjadi padang tandus penuh debu merah.
Tidak hanya perubahan bentang alam, pertambangan kerap mengorbankan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal yang menjadi sumber pangan, air, dan budaya. Kasus-kasus penggusuran tanpa proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) banyak terjadi. Dampak sosial meliputi konflik agraria, kehilangan mata pencaharian, hingga marginalisasi perempuan dan kelompok rentan. Ironisnya, masyarakat yang menolak tambang justru sering dikriminalisasi.
Saat ini, sekitar 80% dari area deposit nikel di Indonesia mengancam habitat 18 spesies satwa ikonik, termasuk anoa, tarsius, maleo, dan burung rangkong. Bahkan, 29% dari kawasan biodiversitas utama (Key Biodiversity Areas/KBA) dan 11% dari Important Bird Areas (IBA) berada di dalam area nikel. Ekspansi tambang tanpa batas ini mempercepat laju kepunahan spesies endemik dan mengganggu keseimbangan ekosistem hutan tropis yang rapuh.
Sektor kehutanan dan sawit, meskipun juga bermasalah, telah mulai menerapkan berbagai skema tata kelola berbasis keberlanjutan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan ISPO/RSPO di sektor sawit. Selain itu, terdapat pendekatan berbasis kawasan seperti High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). Sebaliknya, sektor pertambangan masih jauh tertinggal dalam hal keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi.
Beberapa negara seperti Kanada dan Australia telah menerapkan standar tambang berkelanjutan yang lebih ketat, termasuk pembatasan tambang di kawasan rawan bencana, kawasan konservasi, wilayah adat, dan zona penyangga. Mereka juga memiliki sistem konsultasi publik dan mekanisme pembagian manfaat yang lebih adil. Di Filipina, beberapa area juga telah ditetapkan sebagai No Mining Zones demi melindungi ekosistem sensitif.
Konsep No-Go Mining Zones (NGZ) bukanlah gagasan baru, melainkan penegasan terhadap perlindungan kawasanyang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Lima kategori kawasan yang layak ditetapkan sebagai NGZ antara lain:
Sayangnya, penerapan NGZ masih lemah karena dominasi kepentingan industri. Oleh karena itu, penting untuk membangun peta NGZ partisipatif dan memperkuat kapasitas aktor lokal—termasuk universitas, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil—untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengadvokasi perlindungan kawasan-kawasan kritis tersebut.
Oleh karena itu, melalui “Memungkinkan Kontribusi Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan yang Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan dalam Transisi Energi dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan” Project Auriga Nusantara bersama WWF dengan dukungan Uni Eropa berupaya membuka ruang untuk mendukung organisasi masyarakat sipil agar dapat memainkan peran yang signifikan dalam identifikasi areal keanekaragaman hayati penting sebagai wilayah No-Go Mining Zones.
FSTP ini memiliki fokus khusus pada wilayah lokal dengan ancaman perubahan penggunaan lahan yang tinggi akibat perluasan pertambangan nikel dan batubara, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan kayu. CSO yang melamar harus berbasis di empat provinsi yang diprioritaskan oleh Auriga Nusantara dan WWF-Indonesia: Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan/atau Sulawesi Tengah. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
Selain persyaratan di atas, WWF-Indonesia dan Auriga Nusantara juga akan melakukan penilaian berdasarkan:
WWF Indonesia dan Auriga Nusantara akan mengumumkan penerima dana hibah yang akan didanai selama 6 bulan dengan jumlah maksimal Rp 200.000.000. Transfer dana hibah ditargetkan pada akhir September atau awal Agustus 2025.
Proses ini diselenggarakan sesuai tahapan berikut:
Template proposal pada link berikut: narasi dan budget.
Proposal lengkap dapat dikirim ke alamat email: hilman@auriga.or.id dengan tembusan/cc ke: info@auriga.or.id dan Ari Moch, Arif (arif@wwf.id)