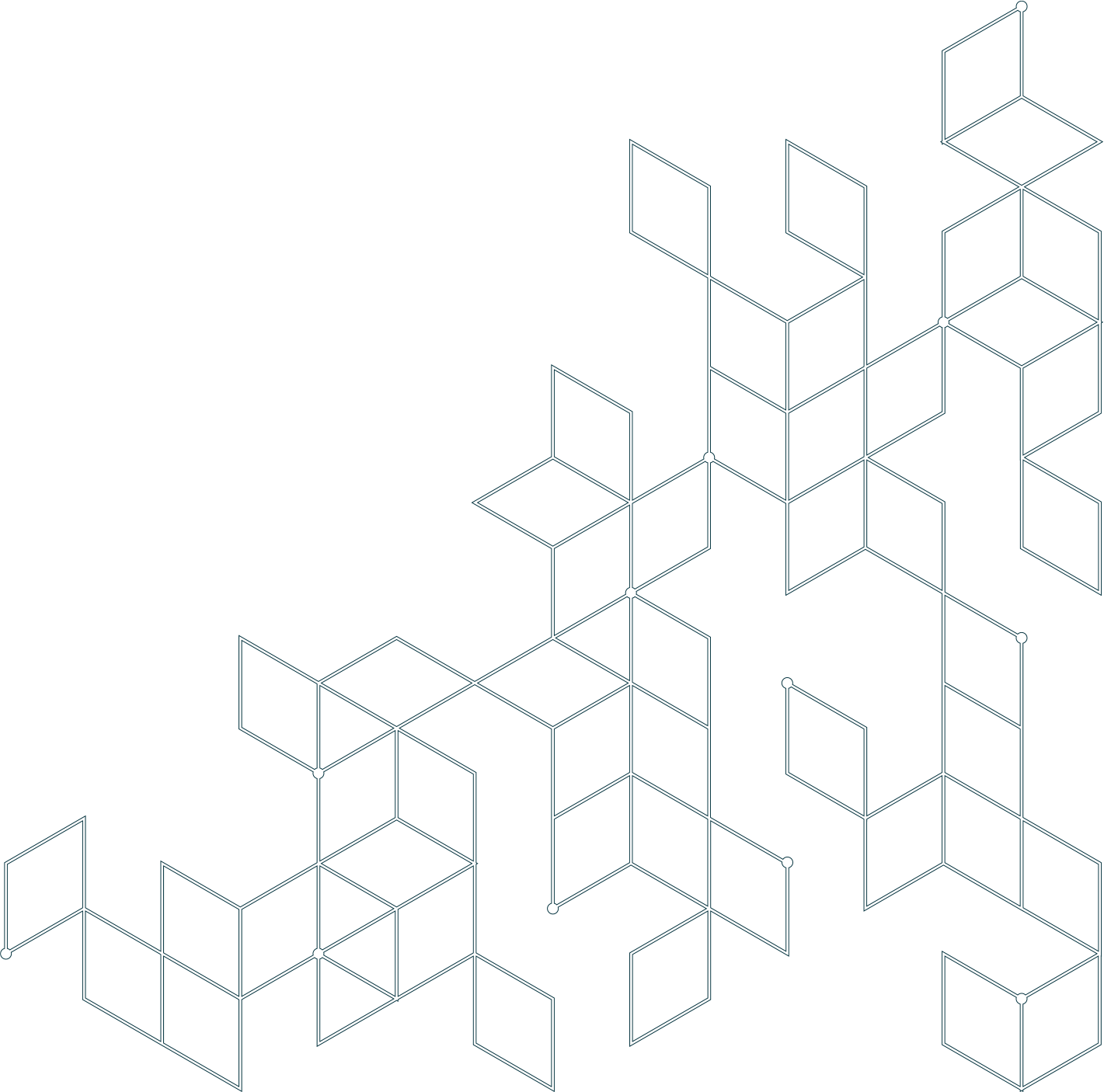Selama dua dekade terakhir, Indonesia mengklaim sebagai contoh negara yang berhasil menurunkan laju deforestasi melalui berbagai kebijakan nasional maupun dukungan internasional. Namun, keberhasilan tersebut mulai menunjukkan gejala kemunduran. Data terbaru dari Auriga Nusantara melalui platform Simontini.id mencatat bahwa luas deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 257.000 hektare, naik menjadi 261.000 hektare pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan terhadap hutan Indonesia kembali menguat, baik oleh ekspansi industri ekstraktif maupun oleh pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar.
Kalimantan Tengah dan Jambi merupakan 2 di antara 10 provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi. Masing-masing memiliki tingkat deforestasi seluas 33.389 hektare dan 14.839 hektare. Meskipun deforestasi terkonsentrasi pada pulau Kalimantan dan Sumatera, geografi deforestasi kini semakin menyebar, termasuk ke kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang muncul sebagai dua provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi, didorong terutama oleh ekspansi tambang nikel.
Pola dan penyebab deforestasi: Spesifik konteks regional
Deforestasi yang terjadi di masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda:
- Jambi mengalami tekanan kuat dari eksploitasi bisnis kehutanan (hutan tanaman industri hak penguasaan hutan alam) dan perkebunan kelapa sawit. Deforestasi di Jambi tidak hanya memicu perubahan lanskap ekologis, tetapi juga memunculkan konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat maupun petani kecil.
- Kalimantan Tengah memperlihatkan tekanan ganda dari sektor HTI, sawit, dan pertambangan batu bara. Ketiganya berkontribusi terhadap hilangnya hutan primer dan sekunder, sekaligus memperburuk kualitas lingkungan hidup, terutama dari sisi kualitas udara dan pencemaran sungai.
- Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan nikel menjadi kontributor utama deforestasi. Sejak lonjakan permintaan global terhadap nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, tekanan terhadap tutupan hutan di Sulawesi meningkat secara signifikan. Tercatat bahwa di ketiga provinsi penghasil nikel utama di Sulawesi (termasuk Sulawesi Selatan), telah terjadi deforestasi seluas 4.200 hektare di area konsesi tambang yang tersebar di 210 titik.
Dampak deforestasi: Lebih dari sekedar hilangnya tutupan lahan
Selama ini, diskursus publik tentang deforestasi kerap terfokus pada angka-angka statistik luas hutan yang hilang, tanpa memperhitungkan multiplier effect yang ditimbulkan oleh hilangnya ekosistem hutan. Padahal, hutan bukan sekadar agregat pohon—ia adalah sistem penyangga kehidupan yang kompleks, menopang keragaman hayati, menyediakan jasa lingkungan, serta menjadi ruang hidup dan budaya bagi jutaan masyarakat lokal dan adat.
- Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Komunitas Lokal: Deforestasi sering kali berjalan seiring dengan penggusuran masyarakat adat atau lokal dari wilayah yang telah mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Masuknya industri skala besar, baik HTI, sawit, maupun tambang, umumnya tidak didahului dengan proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent—FPIC). Akibatnya, banyak komunitas kehilangan akses terhadap lahan, sumber air, dan hutan yang menjadi penyangga hidup mereka. Selain penggusuran, deforestasi juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Lapangan kerja yang dijanjikan oleh perusahaan sering kali bersifat sementara dan tidak layak, sementara kerusakan sumber daya alam membuat masyarakat kehilangan penghidupan jangka panjang, seperti hasil hutan bukan kayu, pertanian lokal, dan perikanan darat.
- Kepunahan dan perusakan habitat satwa: Hutan-hutan di Jambi dan Kalimantan Tengah merupakan habitat penting bagi berbagai spesies endemik dan terancam punah, termasuk orangutan, harimau Sumatera, dan beruang madu. Fragmentasi habitat akibat pembukaan hutan menyebabkan spesies-spesies ini kesulitan mencari makan dan berkembang biak, meningkatkan risiko kepunahan dalam jangka panjang. Di Sulawesi, deforestasi akibat tambang nikel berdampak terhadap spesies seperti anoa, babirusa, dan burung maleo, yang semuanya merupakan satwa endemik Sulawesi. Sayangnya, perhatian terhadap aspek keanekaragaman hayati di wilayah pertambangan masih sangat minim, karena fokus utama hanya pada nilai ekonomi tambang.
- Pencemaran Lingkungan: Hilangnya tutupan hutan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Di Kalimantan Tengah, kegiatan tambang dan perkebunan sering kali menyebabkan pencemaran sungaiakibat limpasan bahan kimia, sedimentasi, dan limbah industri. Ini berdampak langsung pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sungai untuk kebutuhan air bersih, irigasi, dan perikanan. Sementara di kawasan pesisir Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, limbah tambang nikel juga berdampak pada kualitas laut, menurunkan kesehatan terumbu karang dan memicu penurunan hasil tangkapan nelayan. Belum lagi polusi udara dari aktivitas pembakaran lahan maupun pembukaan tambang terbuka yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.
- Konflik Sosial dan Kekerasan Struktural: Masuknya investasi besar ke wilayah hutan tanpa mekanisme konsultasi yang memadai sering kali menimbulkan konflik agraria, baik antara masyarakat dan perusahaan, antar kelompok masyarakat, bahkan antara masyarakat dengan aparat negara. Dalam banyak kasus, masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah justru dikriminalisasi atau menghadapi kekerasan. Konflik-konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga memperlemah kapasitas komunitas untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Situasi ini menjadikan wilayah terdampak deforestasi sebagai kawasan dengan kerentanan sosial tinggi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal lainnya.
Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil lokal (OMS lokal) memegang peran strategis sebagai pengawas independen dan sumber informasi alternatif di tengah minimnya transparansi dari sektor industri maupun pemerintah. OMS lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang mendalam tentang wilayah mereka, relasi sosial-ekonomi masyarakat, serta sejarah konflik dan tata kuasa atas lahan.
Oleh karena itu, melalui “Memungkinkan Kontribusi Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan yang Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan dalam Transisi Energi dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan” Project Auriga Nusantara bersama WWF dengan dukungan Uni Eropa berupaya membuka ruang untuk mendukung organisasi masyarakat sipil agar dapat memainkan peran yang signifikan dalam pemantauan terhadap dampak deforestasi dan ancaman yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber saya alam.
Tujuan dari Dukungan Finansial untuk Pihak Ketiga (FTSP) pada kesempatan ini memiliki banyak sisi, tidak hanya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sipil dan komunitas lokal melalui pemantauan berbasis bukti terhadap perubahan penggunaan lahan dan transisi energi. Kesempatan ini juga untuk mendukung organisasi masyarakat sipil di beberapa bidang penting seperti:
- Dampak deforestasi dan ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, HTI, dan pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah.
- Dampak dan ancaman deforestasi yang ditimbulkan oleh hutan tanaman industri termasuk ekspansi HTI dan perkebunan biomassa di Jambi.
- Dampak dan ancaman deforestasi yang ditimbulkan oleh pertambangan nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
PERSYARATAN UMUM
FSTP ini memiliki fokus khusus pada wilayah lokal dengan ancaman perubahan penggunaan lahan yang tinggi akibat perluasan pertambangan nikel dan batubara, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan kayu. CSO yang melamar harus berbasis di empat provinsi yang diprioritaskan oleh Auriga Nusantara dan WWF-Indonesia: Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan/atau Sulawesi Tengah. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
- Berstatus hukum di Indonesia.
- Merupakan organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi non-pemerintah (NGO, atau kerap disebut Lembaga Swadaya Masyarakat - LSM), Organisasi berbasis komunitas (community-based organisation - CBO), lembaga penelitian, perguruan tinggi.
- Telah dan/atau sedang melaksanakan kegiatan mengenai/terkait transisi energi dan/atau mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan setidaknya selama dua tahun.
- Tidak terafiliasi dengan partai/kepentingan politik.
- Memiliki tata kelola kelembagaan dan keuangan yang baik, termasuk menjalankannya secara bertanggung jawab.
- Diutamakan bagi lembaga yang telah terlibat pelatihan terkait yang diselenggarakan Auriga Nusantara dan WWF Indonesia sebelumnya.
PENILAIAN PROPOSAL
Selain persyaratan di atas, WWF-Indonesia dan Auriga Nusantara juga akan melakukan penilaian berdasarkan:
- Pengalaman berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
- Pengalaman pemantauan pengelolaan sumber daya alam, termasuk perihal pengakuan dan pemenuhan hak kelola masyarakat adat/lokal.
- Pengalaman mengelola dana hibah.
WWF Indonesia dan Auriga Nusantara akan mengumumkan penerima dana hibah yang akan didanai selama 6 bulan dengan jumlah maksimal Rp 200.000.000. Transfer dana hibah ditargetkan pada akhir September atau awal Agustus 2025.
Proses ini diselenggarakan sesuai tahapan berikut:
- WWF Indonesia dan Auriga Nusantara mengumumkan Call for Proposal melalui website.
- Pengajuan proposal dibuka bagi calon organisasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ada.
- WWF Indonesia dan Auriga Nusantara akan menilai dan menyeleksi proposal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- WWF Indonesia akan melakukan proses uji tuntas (due diligence) terhadap mitra terpilih.
- WWF Indonesia and Auriga Nusantara akan mengundang calon mitra terpilih untuk membahas proposal yang diajukan.
- Setelah menyelesaikan proposal, penerima hibah akan menerima pengumuman akhir dan diundang ke proses kontrak.
Jangka Waktu
- 28 - 31 Juli, 2025: Penyusunan proposal naratif oleh para calon.
- 1 Agustus, 2025: Batas waktu penyerahan proposal naratif oleh calon
- 4 - 7 Agustus, 2025: Diskusi dengan kandidat terpilih untuk klarifikasi Proposal Narasi dan proses uji tuntas.
- 8 Agustus, 2025: Pengumuman penerima hibah
STRUKTUR PROPOSAL (MAKSIMAL 15 HAL)
- Judul dan lokasi proyek
- Profil mitra
- Latar belakang masalah
- Tujuan proyek, Sasaran & Strategi
- Kegiatan, hasil yang diharapkan & jadwal
- Struktur tim pelaksana
- Rincian Anggaran (Staff, Operasional, Aktivitas)
Template proposal pada link berikut: narasi dan budget.
PENGIRIMAN PROPOSAL
Proposal lengkap dapat dikirim ke alamat email: hilman@auriga.or.id dengan tembusan/cc ke: info@auriga.or.id dan Ari Moch, Arif (arif@wwf.id)