Masyarakat Menuntut FSC Memastikan Implementasi Pemulihan Penuh atas Kerusakan Wilayah Mereka
Keputusan dan kebijakan FSC akan mempengaruhi pengelolaan hutan dunia, termasuk Indonesia. Apakah kondisi yang dihadapi masyarakat akan selesai, atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk.
AURIGA - Beberapa hari lalu, tanggal 09-14 Oktober 2022, perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, hadir pada Rapat Umum Forest Stewardship Council (FSC- General Assembly) di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Perhelatan berkala yang menjadi momen penting bagi organisasi dengan keanggotaan dari berbagai latar belakang diantaranya non government organization, bisnis, akademisi, peneliti dan masyarakat adat, yang berasal dari lebih 40 negara, yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab.
Mereka hadir untuk menyampaikan kekhawatiran dan menceritakan dampak atas konversi dan eksploitasi hutan alam oleh korporasi besar di wilayah mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menguasai dan merusak wilayah adat yang sangat luas dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang besar. Masyarakat adat yang hadir tersebut berasal dari Sumatera, Kalimantan dan juga Papua.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2021, menunjukkan, lebih dari 11,2 juta hektar kawasan hutan telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk hutan tanaman, dan seluas 18,4 juta hektar PBPH hutan alam, atau sebelumnya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Atas kekhawatiran tersebut, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak FSC memutuskan sesuatu yang akan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat adat. Salah satunya dengan penguatan kerangka kerja pemulihan lingkungan dan sosial (Mosi 45). Mewajibkan semua perusaan yang dalam status disasosiasi dan/atau pendatang baru FSC untuk terlebih dahulu menyelesaikan hingga tuntas persoalan lingkungan dan sosialnya sebelum kembali berasosiasi dengan FSC.

Petrus Kinggo, masyarakat adat asal Dusun Kambenap Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua menyampaikan pesan bagi para pemangku kebijakan sertifikasi hutan, karena mereka telah merasakan dampak buruk pengrusakan hutan, sungai menjadi rusak, hutan tempat berburu pun hilang, dan bencana pun terus bermunculan.
“Kami, menyaksikan bagaimana aktivitas perusahaan sawit dan hutan tanaman industri telah menghancurkan sungai tempat kami mengambil air, hutan tempat kami memperoleh makanan dan rumah”, “Masyarakat adat itu, hidupnya menyatu dengan tanah dan hutan, kalau hutannya hilang, kita hidup bagaimana” tegas Petrus.
Keputusan dan kebijakan FSC akan mempengaruhi pengelolaan hutan dunia, termasuk Indonesia. Apakah kondisi yang dihadapi masyarakat akan selesai, atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk.
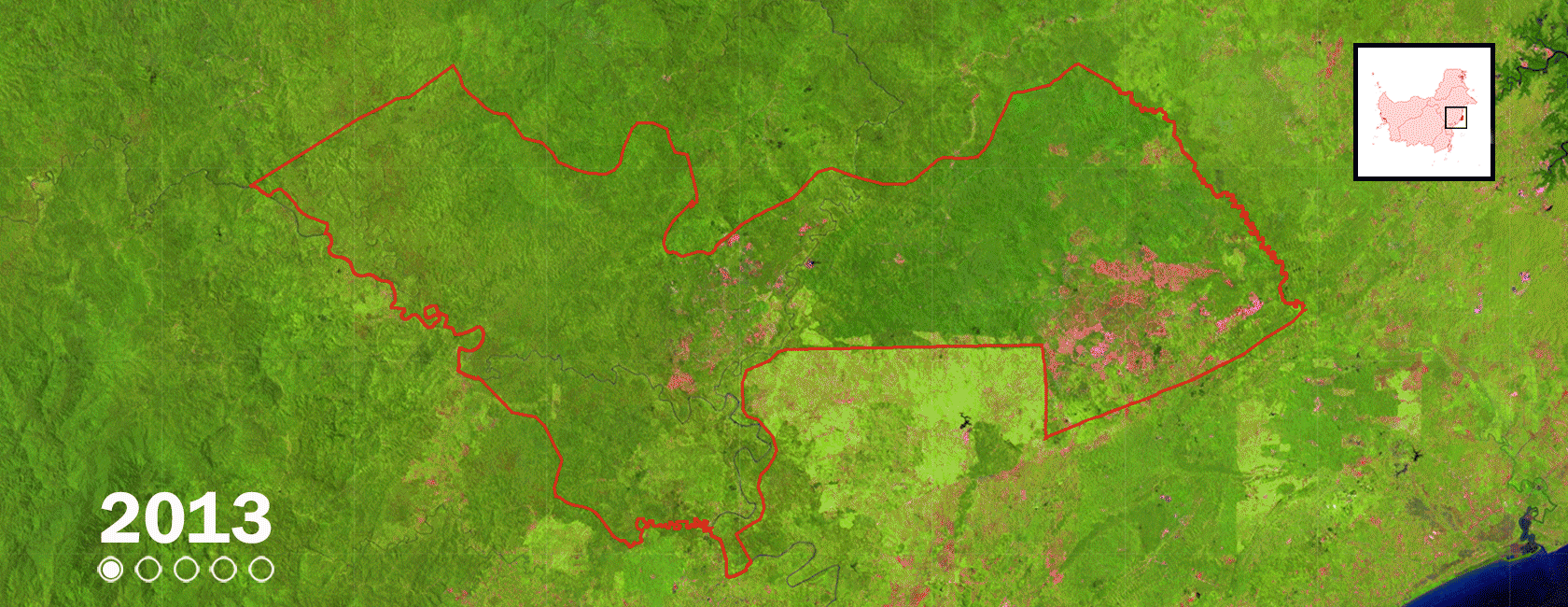
Deforestasi yang ditengarai terjadi di konsesi PT Fajar Surya Swadaya (FSS), anak usaha Djarum Grup, di Kalimantan Timur. Salah satu anak usaha Djarum Grup, yakni PT Bukit Muria Jaya (BMJ), tadinya bersertifikat FSC. Auriga Nusantara menyampaikan keluhan ke FSC atas sertifikat tersebut karena terhubung dengan (deforestasi) FSS, dan pada Desember 2020 FSC menghentikan sertifikat BMJ. Foto/animasi: Auriga Nusantara, berbasis citra satelit Landsat.
Perubahan batas waktu konversi hutan (deforestasi) dari tahun 1994 menjadi tahun 2020, telah membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan yang telah membuka lebih dari 2 juta hektar hutan alam Indonesia dan berkonflik dengan ratusan Masyarakat Adat maupun masyarakat tradisional, seperti, Asia Pulp and Paper (APP), APRIL, Djarum dan Korindo untuk dapat kembali bergabung, dan mendapatkan keuntungan dari sertifikasi ini. Kondisi ini menempatkan reputasi FSC dalam pertaruhan, jika peluang bergabungnya perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tidak dibarengi dengan implementasi secara utuh dan pemantauan yang ketat pelaksanaan kerangka pemulihan lingkungan dan sosial.
Terkait itu, Sugiarto, masyarakat Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengharapkan, Penilai Independen harus dilibatkan sejak awal saat mengidentifikasi pemangku kepentingan atau pemegang hak yang terdampak dan area terdampak. Informasi harus disampaikan secara utuh dan dapat diakses publik. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya keberpihakan pihak ketiga, ketidak adilan dan mencegah persetujuan dengan paksaan.
Aidil Fitri dari Hutan Kita Institute (HaKI) yang hadir sebagai pembicara saat itu mengatakan persoalan konversi dan pemulihan merupakan isu penting. Sebab persoalan hari ini adalah isu kepercayaan terhadap korporasi dan juga sertifikasi.“Kami, menaruh harapan pada FSC, untuk menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat”.
Isu kinerja keberlanjutan serta penyelesaian persoalan sosial di tingkat tapak seharusnya menjadi acuan dalam segala pertimbangan FSC. Mulai dari penyusunan dan penetapan kerangka kerja pemulihan hingga pelaksanaannya. Ke depan, implementasi atas kerangka pemulihan akan menjadi ukuran, apakah FSC dapat mengontrol pemegang logo-nya untuk melakukan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab atau tidak. Jika tidak, FSC akan kehilangan reputasinya sebagai skema pelindung hutan dan masyarakat adat dunia.
Perlindungan terhadap hak masyarakat adalah penting dalam setiap upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. "Masyarakat adat adalah perawat hutan terbaik, dimana mereka merawat, menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumber penghidupan mereka", Martha Doq, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, yang hadir di Nusa Dua mendampingi masyarakat adat Long Isun yang terdampak dari perusahaan HPH milik Harita Group di Mahakam Hulu.
Narahubung ;
- Supintri Yohar (Auriga) : +62 813-7349-9788
- Martha Doq (Nurani Perempuan) : +62 811-5861-244
- Hairul Sobri (HaKI) : +62 812-7834-2402

